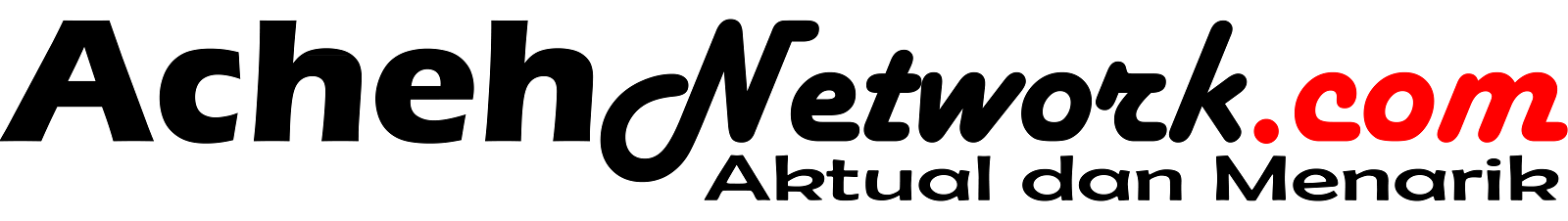Lagenda Asal Mula Suku Mante: Menelusuri Jejak Suku Tertua yang Diketahui Dalam Sejarah Aceh
 |
| Ilustrasi Suku Mante (Foto: Ricardo Stuckert via bobo.grid) |
Pada awal abad ke-20, sungai ini masih jernih seperti yang diceritakan oleh para orang tua di kampung. Sekitar sungai masih terdapat hutan perawan yang terhubung dari pengunungan Seulawah di utara hingga Leuser di selatan.
Bahkan, jika ditarik garis kesambungan, hutan ini meliputi seluruh gugusan bukit barisan hingga ke ujung selatan Sumatera.
Pada gundukan pasir tersebut, terdapat sampah berupa ranting dan dedaunan yang jika diangkat akan terdapat udang segar atau ikan. Alam memberikan segalanya pada masa itu.
Nekmi menceritakan kembali cerita dari Neknyang (nenek buyut), bahwa suatu pagi beberapa anak kampung Mon Mata berkeinginan untuk melihat "Aneuk Lacoe", yang bisa disebut kurcaci atau hobbit dalam bahasa kita saat ini.
Mereka membuat gelang dari rotan, lalu melemparkan gelang-gelang tersebut ke gundukan pasir di tengah sungai dan bersembunyi di tempat yang lebih jauh.
Mereka menunggu dengan sabar hingga hampir bosan, tiba-tiba dari kejauhan muncul beberapa kurcaci yang hanya mengenakan cawat.
Mereka sangat senang dengan gelang-gelang tersebut. Mereka memasangkannya di tangan dan kaki dengan penuh kegembiraan.
"Aneuk Lacoe" adalah makhluk gaib yang mempesona bagi anak-anak kampung Mon Mata.
Mereka diyakini memiliki kemampuan sihir dan bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan di hutan.
Namun, berbeda dengan suku-suku lain di Aceh, mereka tidak bergaul dan memilih menghindari peradaban. Menurut saksi mata, ukuran "Aneuk Lacoe" tidak pernah melebihi satu meter.
Sebagian besar dari mereka memiliki tinggi seperti balita berusia lima tahun.
Namun, jangan meragukan keaktifan mereka. Begitu mendengar suara langkah kaki atau ranting yang patah tertindih, mereka segera melarikan diri ke dalam hutan.
Anak-anak kampung hanya bisa memandang mereka dari jauh tanpa pernah bisa mendekatinya.
Jembatan Krueng Sabee
Di daerah Krueng Sabee dan sekitarnya terdapat sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa anak kecil atau orang yang tidak berpakaian akan disebut sebagai "aneuk lacoe".
Fenomena munculnya kurcaci atau Hobbit ini bukan hanya terjadi di daerah Krueng Sabee, tetapi juga di sepanjang sungai-sungai besar di sebelah selatan seperti Sungai Krueng Teunom, Krueng Woyla, Krueng Seunagan, serta banyak sungai berbatu lainnya.
Penduduk sekitar menyebut mereka sebagai Orang Bante atau Orang Mante.
Pada tahun 1940-an, Orang Mante tidak lagi terlihat turun ke sungai-sungai di pesisir Barat Aceh.
Asal usul suku Mante ini dijelaskan oleh H.M. Zainuddin, seorang pujangga dan sejarawan dalam bukunya yang monumental, "Tarikh Aceh dan Nusantara" yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1961.
Ia menyebutkan bahwa bangsa Aceh termasuk dalam lingkungan bangsa Melayu, yang terdiri dari bangsa-bangsa seperti Mante (Bante), Lanun, Sakai Jakun, Semang (orang laut), Sanun, dan lain-lain.
Etnis-etnis tersebut memiliki hubungan dengan bangsa Phonesia di Babylonia dan bangsa Dravida di lembah sungai Indus dan Ganges.
Menurut penjelasan H.M. Zainuddin, bangsa Mante terutama berada di Aceh Besar.
Berdasarkan cerita dari orang tua, mereka berkedudukan di kampung Seumileuk yang disebut sebagai kampung Rumoh Dua Blah (Kampung Rumah Dua Belas), terletak di atas Seulimeum antara kampung Jantho dan Tangse. Seumileuk berarti daratan yang luas.
Bangsa Mante ini berkembang biak di seluruh lembah Aceh tiga segi dan kemudian berpindah ke tempat lain.
Lembah Aceh Besar (Aceh tiga segi) pada masa itu memiliki laut Indrapuri dan Tanoh Abee sebagai tempat tinggal orang Hindu.
Blang Bintang, Ulee Kareng, Lam Baro, Lam Ateuk, Lam Nyong, Tungkop, Lam Nga, Tibang, dan lain-lain merupakan laut yang luas.
Menurut cerita tersebut, pelabuhan bagi orang yang ingin berhaji adalah di Aneuk Gle, Montasik, tempat di mana pelaut-pelaut mengambil air dari perigi.
Saat ini, Kampung Montasik terletak di tepi laut, sementara Kampung Ateuk berasal dari kata "Gateuk", yang merujuk kepada ketam tanah yang hidup di air asin (payau) di sekitar laut.
Pasar terbesar berada di sekitar Kuta Masah di atas Indrapuri.
Informasi tersebut menunjukkan bahwa hingga abad ke-8 Masehi, pantai atau tepi laut Aceh Besar mencapai dekat Indrapuri dan Tanoh Abee, membentuk sebuah teluk yang indah.
Meskipun letak geografisnya telah berubah seiring pergeseran bumi, kehidupan masyarakat Aceh pada masa lalu yang masih berpindah-pindah belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh H.M. Zainuddin.
Sejarah Suku Mante
Kisah yang mengelilingi suku Mante menjadi salah satu cerita menarik dalam sejarah Aceh.
Menurut catatan sejarah yang paling lengkap, yang disusun oleh Dada Meuraksa dalam "Ungkapan Sejarah Aceh" pada tahun 1975, dinasti Mante dianggap sebagai dinasti tertua yang diketahui.
Pusat kerajaan Mante terletak di Seumileuk, sebuah daerah pedalaman di Seulimeum antara Jantho, masih dalam wilayah sagi XXII mukim.
Kata "Mante" sendiri diyakini berasal dari "Mantenia" atau "Mantinea", sebuah kota di Yunani yang penduduknya disebut Mantinean.
Pada abad ke-14 SM, mereka melakukan perpindahan penduduk ke daerah yang lebih hangat di selatan.
Awalnya, mereka tinggal di Pulau Kreta bagian selatan, yaitu di Thessalia, dan suku mereka disebut Achaea.
Namun, pada abad ke-12 SM, mereka diusir oleh suku Doris, sehingga mereka bermigrasi ke wilayah Peloponnesus Utara, sebagian ke Asia Kecil (Turki), dan sebagian lainnya menuju Asia Tengah (lembah Kaukasus).
Kelompok yang bergerak ke lembah Kaukasus kemudian melanjutkan perjalanan ke timur melalui Chaibar Pass, sebuah jurang di perbatasan Afganistan dan India, dan mencapai bagian utara India.
Di sana, mereka bercampur dengan penduduk setempat.
Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke selatan, menyeberangi Selat Malaka, dan akhirnya mencapai Pulau Perca (Sumatera).
Mereka mendirikan Kerajaan Mante dengan pusat di Seumileuk, sebuah lokasi yang strategis untuk mendapatkan sumber emas di kaki Gunung Emas, di mana tiga sungai bercabang: Sungai Krueng Aceh, Krueng Woyla (Tutut), dan Krueng Keumala.
Seumileuk terletak di lembah Krueng Aceh, dan kemungkinan kata "Aceh" dalam lembah Aceh (Aceh Raya), Krueng Aceh, dan bangsa Aceh berasal dari nama suku mereka, Achaia.
Meskipun catatan sejarah tidak mencatat semua raja dari dinasti Mante yang memerintah di lembah Aceh Besar, kita mengenal seorang raja bernama "Maharaja Po Tuah Meuri".
Namun, raja-raja sebelumnya tidak diketahui secara pasti.
Setelah Maharaja Po Tuan Meuri, penerusnya dalam garis keturunan termasuk Maharaja Ok Meugumbak, Maharaja Jagat, Maharaja Dumet, dan Maharani Putro Budian.
Dinasti Mante berakhir pada periode ini, dan setelahnya sejarah tidak lagi mencatat dinasti suku Mante.
Maharani Putro Budian menikah dengan Maharaja Po Liang, seorang bangsawan Campa dari Indocina yang datang ke Aceh bersama rombongannya karena negerinya diserang oleh musuh yang lebih kuat.
Dalam perjalanan mencari tanah air baru, Maharaja Po Liang dan Maharani Putro Budian berhasil membudhakan Aceh dengan mengembangkan agama Budha mazhab Hinayana sekte Mantrayana.
Akhirnya, Po Liang diangkat sebagai Raja Lamuri pertama.
Berlanjut dengan dinasti Po Liang yang memerintah Kerajaan Aceh Lamuri, sejarawan Dada Meuraksa mencatat sejumlah raja, termasuk Raja Lamuri Budha I, II, III, dan IV.
Namun, kemudian dinasti berubah saat Raja Lam Teuba, yang juga dikenal sebagai Raja Lamuri Islam I, memeluk Islam mazhab Syiah.
Raja Lam Teuba terkenal karena keberaniannya, keadilan, kecerdasannya, dan terutama karena menerima agama Islam yang diperkenalkan kepadanya oleh seorang keturunan Sayid dari Rasulullah pada tahun 754 M.
Penerus Raja Lam Teuba dalam dinasti Syiah adalah Raja Gading, Banda Chairullah, Cut Samah, Cut Madin, Cut Malim, Cut Seudang, Cut Samlako, Cut Ujo, Cut Wali, Cut Ubit, Cut Dhiet, Cut Umbak, dan Putro Ti Seuno.
Dinasti ini berakhir ketika Putro Ti Seuno menikah dengan Johan Syah, yang kemudian menjadi Sultan Alaidin Johan Syah, Raja Lamuri Islam Ahlussunnah Wal Jamaah pertama pada tahun 1205-1235 M.
Setelah itu, dinasti Alaidin menggantikan dinasti Lamuri, dan Aceh Darussalam menjadi nama yang diberikan pada kerajaan tersebut.
Mengapa suku Mante menghilang dari pusat kehidupan kosmopolitan di Aceh tetap menjadi misteri.
Diduga sebagian dari mereka memilih hidup mengembara di pedalaman hutan saat Aceh mulai memeluk agama Budha pada awal masa dinasti Po Liang.
Alasan dan nasib pasti suku Mante setelah itu masih menjadi pertanyaan yang menarik dalam sejarah Aceh.
Harga Diri Suku Mante
 |
| Perkiraan wajah Aneuk Lacoe atau Suku Mante menyerupai manusia purba Homo Naledi |
Pada saat itu, dua individu dari suku Mante ditangkap, diduga sebagai sepasang suami istri.
Meskipun ditahan, mereka enggan berbicara atau makan, memilih untuk mati kelaparan.
Kejadian ini membuat Sultan Ali Mughayat Syah merasa menyesal dan ia menangis atas kematian kedua Mante tersebut.
Ia kemudian mengeluarkan maklumat kepada rakyat Aceh untuk tidak mengganggu suku Mante apabila bertemu dengan mereka.
Keberadaan suku Mante di pedalaman Aceh telah menjadi subjek perdebatan yang sengit di kalangan banyak orang.
Ada yang mempercayai dan ada pula yang meragukan keberadaan mereka.
Mungkin ada yang bersikap sinis dan menganggapnya sebagai dongeng semata. Bagi masyarakat Aceh, suku Mante seperti sebuah legenda atau mitos, karena jarang sekali orang yang benar-benar bertemu dengan mereka.
Suku Mante sendiri termasuk dalam suku Proto Melayu atau yang dikenal sebagai Melayu Tua, yang diyakini telah punah.
Namun, adakah kemungkinan suku Mante kembali ditemukan? Dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers", Snouck Hurgronye mencatat bahwa meskipun dirinya sendiri belum pernah bertemu dengan suku tersebut, beberapa saksi mengklaim pernah melihat Mante.
Mereka menyebutkan bahwa suku ini sering ditemukan di pedalaman Lokop Aceh Timur dan daerah tersembunyi di Tangse Pidie.
Snouck Hurgronye sendiri menafsirkan istilah Mante sebagai perilaku yang konyol dan kekanak-kanakan.
Misteri seputar suku Mante dan keberadaan mereka terus mengundang minat dan rasa ingin tahu.
Apakah mereka benar-benar masih ada di pedalaman Aceh? Ataukah mereka hanya menjadi bagian dari imajinasi kolektif?
Mungkin dengan eksplorasi lebih lanjut dan penelitian yang mendalam, kita dapat menyingkap kebenaran yang tersembunyi di balik kisah-kisah yang berkembang tentang suku Mante.
Selamatkan Hutan dan Alam
Mari kita selamatkan hutan, mari kita selamatkan alam.
Suku Mante telah memilih jalan kehidupan yang berbeda dengan meninggalkan kehidupan perkotaan dan memilih untuk hidup di dalam hutan.
Dalam mengingat pesan yang pernah disampaikan oleh Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah, apa untungnya kita mengganggu mereka?
Di zaman yang modern ini, nasib suku Mante tidak jauh berbeda dengan flora dan fauna yang hidup di dalam hutan.
Mereka tidak berdaya menghadapi serbuan perusahaan-perusahaan besar yang menggerus habitat mereka.
Perkebunan sawit, karet, dan yang lebih memprihatinkan adalah penebangan hutan oleh korporasi dengan kedok perkebunan sawit dan karet.
Aktivitas penambangan emas, eksploitasi gas, dan penebangan hutan secara besar-besaran telah mendesak mereka ke sudut terakhir.
Para pemilik modal yang serakah hanya memikirkan keuntungan ekonomi semata.
Namun, apakah hidup hanya sebatas materi dan keserakahan semata?
Ketika pemimpin-pemimpin di Aceh yang lahir dari demokrasi memilih menutup mata mereka demi mendapatkan fee belaka, suku Mante dipastikan akan punah! Dan betapa kita merindukan seorang pemimpin seperti Alaidin Ali Mughayat Syah, yang memahami pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam.
Nekmi bercerita suatu hari Nek Nyang dengan penuh kegembiraan menceritakan pengalamannya.
Ia menceritakan tentang saat ia melihat suku Mante tertawa bahagia dengan gelang-gelang rotan mereka.
Suara mereka yang keras terdengar sangat asing, membuat para anak-anak dari kampung Mon Mata yang mengintip dari kejauhan bergerak mundur dan menahan nafas mereka.
Namun, mereka melihat betapa bahagianya suku Mante dengan kehidupan mereka yang berbeda.
Pemandangan tersebut begitu memukau, sementara aliran sungai Krueng Sabee yang mengalir pelan dengan buih-buihnya melaju menuju lautan.
Sungguh indahnya alam yang ada di sekitar kita.
Mari kita hargai dan lestarikan keberagaman alam dan kehidupan suku Mante.
Mari kita bersatu untuk menyelamatkan hutan dan menjaga keindahan alam ini agar tetap abadi bagi generasi mendatang.
Karena hanya dengan melindungi alam, kita juga melindungi harga diri kita sebagai manusia yang bijak dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita.(*)